Pulang dari acara buka bersama, saya menyempatkan diri mampir ke minimarket untuk membeli cemilan dan sekaleng kopi. Pada saat antri di kasir, saya dapati pembeli lain dengan belanjaan yang kurang masuk akal kalau untuk dihabiskan dalam satu malam. Sirup empat botol, segepok permen, dua lodong astor dan satu gembrengan biskuit. Mata saya kemudian menerawang di balik pintu kaca minimarket sambil bergumam: “inikah yang dimaksud ‘hilal’ sudah terlihat?”.
Di daerah saya, untuk mengenali tibanya Hari Raya Idul Fitri sangatlah mudah. Ada beberapa gejala visual yang selalu terjadi: lihat orang belanja siang malam, lihat kembang api, lihat manusia dimensi lain jual uang baru, lihat beras, dan lihat orang-orang minta maaf tapi masih tidak sadar salahnya di mana. Jika semua gejala itu sudah terjadi, maka sudah bisa dipastikan lebaran jatuh pada esok harinya.
Hal ini kontras sekali dengan yang saya tahu di Tajikistan melalui buku Garis Batas (Agustinus Wibowo). Tepatnya di Yamchun ada dialog yang menarik, persis saya kutip dari buku seperti ini:
“Kakak,” saya berseru ke arah para pemandi, “suka sekali ya berendam di air panas?”Padahal beliau (Agustinus Wibowo) ini juga seorang muslim yang sedang di negeri mayoritas muslim pula. Namun penggambaran kondisi di Asia Tengah itu benar-benar berbeda sekali dengan Indonesia. Ketika kita berdebat elok tentang warung makan yang buka siang atau tentang satu dua gelintir kalimat “hormati yang tidak puasa”, ternyata di Dushanbe dan Istaravshan umat muslim enjoy saja menenggak vodka di pinggir jalan meski saat bulan puasa. Jadi yang diperdebatkan di awal puasa dulu tidak perlu dan tidak mutu.
“Hari ini hari libur. Jadi kami segerombolan menyewa mobil jauh-jauh dari Ishkashim,” kata seorang dari mereka.
Hari libur? Hari libur apa?
“Masa kau tak tahu? Ini adalah hari Idul Fitri. Hari Raya penting bagi umat Muslim,” jawabnya.
Minal ‘Aidin wal Faizin, kalimat yang sering diucapkan setiap lebaran. Arti ucapakan itu sebagaimana yang kita tahu adalah ‘kita kembali dan meraih kemenangan’. Bagi saya ini cukup menarik untuk diperbincangkan. Saya meyakini kekuatan sebuah bahasa mampu mengkonstruksi budaya dari akar hingga ke seluruh cabangnya. Istilah ‘kemenangan’ rasanya memang sepele, tapi prakteknya ternyata tidak sesepele itu.
Masyarakat kita entah mengapa mengartikan kata ‘kemenangan’ dengan sangat rigid. Dalam banyak kejadian ‘kemenagan’ bisa disebutkan dalam beberapa konteks seperti kemenangan perang, kemenangan pertandingan, kemenangan cinta dan lain-lain. Dan belum lengkap disebut sebagai sebuah kemenangan kalau belum disimbolkan dengan perayaan. Kalau dalam masyarakat Jawa biasanya ada yang namanya tradisi syukuran, yaitu sebuah upacara yang melambangkan rasa syukur.
Alih-alih khusyuk menangis tersedu-sedu disela sujud malam, kemenangan ini dirayakan dengan pesta hedonistik. Simbol-simbol hedon ini bisa kita lihat dari gejala-gejala yang terjadi menyambut Idul Fitri. Misalnya kita lihat meriahnya petasan dan kembang api. Sekian ribu dijajakan untuk kenikmatan semata melihat indahnya letupan kembang api. Bahkan anak-anak yang lebih futuristik cenderung memilih petasan (entah estetisnya di mana) sebagai pemicu kesenangan mereka. Jangan kira ini hanya ulah isengnya anak-anak. Orangtua yang tidak melarang juga menjadi bagian dari pendidikan hedon usia dini.
Apalagi jika kita menelisik Jasa Tukar Uang Baru. Dilihat dari segi manapun kita akan temukan simbol hedonis nan materialis yang kuat. Bagaimana tidak, orang-orang rela ‘membeli’ uang yang sebenarnya nominal dan nilainya sama. Hanya demi sebuah kebaruan yang kalau dikasihkan ke orang lain biar kelihatan sedikit lebih elok. Dari sini kita temukan bagaimana uang pun nilai tukarnya bisa berubah jika dilihat dari segi fisiknya. Entah kenapa masyarakat kita suka menghindari substansi dan menjadi penghamba ‘kulit luar’.
Belum cukup dengan itu, dalam upaya menjadikan Idul Fitri sebagai hari se-perfect mungkin, orang-orang berburu kemegahan melalui busana dan asesorisnya. Gejala satu ini ibarat gado-gado komplit, sudah hedonis dan materialis ini masih dilengkapi konsumeris pula. Bagi pemilik modal jelas ini makanan empuk. Tinggal buka lapak bertuliskan ‘diskon’
Jika melihat fenomena-fenomena itu saya merasa Hari Raya kok lebih fana dari Hari Kemerdekaan. Bicara religiusitas juga tidak penting lagi, karena tingkat ketaqwaan sudah seolah terwakili oleh pakaian bersih, baru, model kekinian dan semerbak wewangian surga. Para lakik tampil dengan baju koko yang dipadukan dengan celana skinny, belibet gelang dan potongan rambut undercut seolah mencitrakan sosok bad boy surgawi. Kalau sudah begini mustahil kalau mau membicarakan tragedi di Turki, karena Piala Eropa jelas lebih menarik.
Tapi mau bagaimana juga perayaan ini sudah mendarah daging di kebudayaan kita. Kalau diusik bisa-bisa kena gampar. Tulisan ini juga tak ada maksud untuk merendahkan, meremehkan atau mengusik kefanaan yang sudah mapan. Hanya unek-unek yang barangkali ada yang setuju. Sebab saya getir sekali, semakin ke sini untuk merayakan Idul Fitri kok foya-foyanya makin dahsyat. Seolah kalau belum membelanjakan uang besar-besaran takut ibadah Ramadhannya tidak diterima Gusti Allah. Lebih getir lagi kalau hedonnya ini takut dicap ‘orang tak mampu’ oleh keluarga atau tetangga alias GENSI. Duhhh.. Mau kembali suci kok mekso men.

.png)




.jpg)


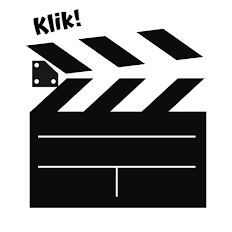

Hihi. Ilham, aku baca tulisanmu seperti melihat kertas warna hitam dan putih padahal warna itu banyak.
BalasHapusKalo pendapatku yo ham, ini perkara tradisi, dan inilah keunikan indonesia. Memang ga dipungkiri banyak yg menyambut lebaran dgn persiapan kemewahan dr baju, properti rumah dsb demi gengsi. Tapi nggak semua seperti itu kok. Kadang saking istimewanya sesuatu, rasanya ingin memberikan yg terbaik. Misal nih kamu pengen ketemu cewekmu dihari kalian udah berbulan2 ga ketemu kan pasti rasanya ada dorongan untuk memberi yg terbaik kan, entah baju yg kamu pakai, entah tempat yg paling romantis, meskipun tau dia bakal terima kamu apa adanya. Aku melihatnya sih ngono ham. Sing penting sih yo emang sing mbok omongke mau sih "ojo mekso". Nak pas due duet rapopo nak ora yo orasah wae. Terus masalah mercon, dibilang seneng, yo kadang anyel. Pie yo, menurutku cuma pengawasan ke anak2 aja sih biar ngati2 n milih mercon sing ringan2 wae. Plus ngurupkene ojo kerep2 n nonton2 tonggone enek sing due loro jantung ora :D
Pokoke nak pas idul fitri ngene rasane seneng. Rame soale
Unek-unekmu jero Ham. Mudah2 an dipahami orang banyak.
BalasHapusNek aku memang merindukan lebaran jaman kecil. Kumpul bareng keluarga, berkunjung ke tetangga satu persatu sambil menikmati masakan mereka.
Lebih terasa kebersamaannya. Sekarang malah udah gak ada. Habis sholat id cukup kumpul di depan mushola, saling salaman. Lebih praktis tapi berasa ada yg kurang..yaitu keakraban.
Aku kok malah rindu yg spt itu ya.
Qeqeqe.
Dari beberapa tempat yg pernah kutinggali, lebaran di sini lebih sederhana sih, dr lebaran di seberang sana yg hidangannya ampun-ampunan meriahnya.
Lebaranku juga gak ada baju baru Ham,qiqiqi.
Hmm.. Opini yang menarik...
BalasHapusEmang sekarang semua itu seakan menjadi budaya mutlak perayaan Idul Fitri di Indonesia ms...
Saya pun agak setuju dengan opini sampeyan yang entah mengapa begitu melihat fenomena semacam itu (mall rame menjelang lebaran & tradisi harus baru)...
Betul yang disampaikan Mbak Fubuki di komen atas.. Yang jadi masalah adalah yang berlebih-lebihan dan menjadikan budaya tersebut sebagai KEWAJIBAN...
Nice artikel, saya juga sependapat denngan agan...
BalasHapusTidak suka dengan hal-hal yang berlebihan..