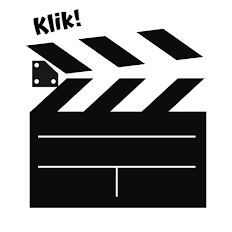Perkenalan saya dengan kota Solo berawal dari hal embuh yang pernah saya lakukan tatkala pakaian sekolah masih tersimbolkan dengan seragam putih-biru. Kala itu, teman saya yang bernama Nega mengajak mencari buku panduan game Seal. Memang, saat saya SMP dulu suka sekali dengan Seal Online meski levelnya stuck dibelasan saja. Sementara Nega sudah jauh lebih pro. Kegandrungan itulah yang membuat kami terpacu untuk meluncur dari Kartasura ke Solo dengan kayuhan sepeda. Jar kendhel!
Kami mencari di beberapa lokasi, seperti warnet Yahoo!, Solo Grand Mall, Gramedia, dan tempat-tempat lain yang saya lupa namanya. Jujur saja, saat itu masih ada rasa was-was jika saya tidak bisa pulang. Sebab, kota Solo masing sangat asing bagi saya.
Kekhawatiran saya berbuah lega ketika sekujur tubuh ini tiba di rumah. Lalu apa kami mendapat buku panduan tersebut? Tidak! Tidak ada di mana-mana. Justru saya malah membawa oleh-oleh berupa luka karena sempat terjungkal di jalan. Tapi nek dipikir-pikir pancen kemlinthi tenan. Ngonthel sepeda dari Kartasura sampai Solo. Tur durung adus sisan. Joss bloko-bloko!
Selang beberapa semester setelahnya, saya kembali dolan ngetan bersama kawan saya yang lain. Kali ini kepentingannya adalah untuk nonton di bioskop. Sopoyono, saat itu kami yang masih belia ini diburu oleh polisi lalu lintas. Alasannya sudah jelas. Saya tidak memakai helm dan dari perawakan terlihat kami adalah bocah-bocah tak berizin. Alhasil, diseretlah kami ke pos polisi.
Setelah ditanya macam-macam, diketahuilah bahwa teman saya ini memiliki bapak seorang polisi juga. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Pak Polisi untuk menjatuhkan denda kepada kami. Maka terjadilah perdebatan sengit soal harga yang mana kala itu saya cuma ndomblong saja. Singkat cerita, kami menyerah pada nominal 170.000 rupiah. YA! SATUS PITUNG PULUH EWU! Azu!
Lah kok mau-maunya? Lha mana kutau harga semestinya berapa, Bosku? Kuwi jik SMP. Otakku masih berkutat dengan nama-nama kerajaan di Indonesia. Jingseng!
Terlepas dari pengalaman nyelekit itu, saat kelas tiga SMP saya memiliki hobi main ke Solo sendirian. Yuhuu. Jadi ceritanya, setiap hari minggu saya pergi ke Gramedia dengan naik bus. Memang tidak langsung turun tepat di depan toko buku ternama itu. Sebab, tepat di depannya ada jalan searah yang harus dipatuhi. Alhasil, saya dari Kartasura turun di perempatan Gendengan atau kadang kelupaan mblabas sitihik sampai Lapangan Kota Barat.
Dari turun bus itulah saya memutuskan untuk jalan kaki hingga sampai di Gramedia. Pulangnya pun sama saja. Tingkah laku ini lumayan rutin saya lakukan setiap minggu, namun berakhir hingga awal-awal saya masuk SMA. Eits, jangan kira saya ke Gramedia buat beli buku. Ya cuma baca sampelnya dong, Bos. Cah irit og.
Begitulah kira-kira perkenalan saya dengan kota Solo semasa SMP. Sedang pengalaman saya ke Solo saat duduk di bangku SMA terhitung lebih sering tapi tidak rutin. Sebut saja misalnya kunjungan saya ke acara pensi, acara pameran komputer, acara lomba, serta mencari sponsor untuk acara ulang tahun sekolah.
Ada pula saat saya terlibat dengan komunitas menulis, eh tapi cuma datang pada satu kali rapat dan workshop. Niat hati ingin aktif benar, tapi keadaan kurang merestui. Sebab lokasi kumpul lebih jauh daripada tempat saya mbolos. Ya, tempat mbolos saya tak lain dan tak bukan adalah Balkon SGM, tempat main billyard. Jago billyard? Babar blas!
Kami mencari di beberapa lokasi, seperti warnet Yahoo!, Solo Grand Mall, Gramedia, dan tempat-tempat lain yang saya lupa namanya. Jujur saja, saat itu masih ada rasa was-was jika saya tidak bisa pulang. Sebab, kota Solo masing sangat asing bagi saya.
Kekhawatiran saya berbuah lega ketika sekujur tubuh ini tiba di rumah. Lalu apa kami mendapat buku panduan tersebut? Tidak! Tidak ada di mana-mana. Justru saya malah membawa oleh-oleh berupa luka karena sempat terjungkal di jalan. Tapi nek dipikir-pikir pancen kemlinthi tenan. Ngonthel sepeda dari Kartasura sampai Solo. Tur durung adus sisan. Joss bloko-bloko!
Selang beberapa semester setelahnya, saya kembali dolan ngetan bersama kawan saya yang lain. Kali ini kepentingannya adalah untuk nonton di bioskop. Sopoyono, saat itu kami yang masih belia ini diburu oleh polisi lalu lintas. Alasannya sudah jelas. Saya tidak memakai helm dan dari perawakan terlihat kami adalah bocah-bocah tak berizin. Alhasil, diseretlah kami ke pos polisi.
Setelah ditanya macam-macam, diketahuilah bahwa teman saya ini memiliki bapak seorang polisi juga. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Pak Polisi untuk menjatuhkan denda kepada kami. Maka terjadilah perdebatan sengit soal harga yang mana kala itu saya cuma ndomblong saja. Singkat cerita, kami menyerah pada nominal 170.000 rupiah. YA! SATUS PITUNG PULUH EWU! Azu!
Lah kok mau-maunya? Lha mana kutau harga semestinya berapa, Bosku? Kuwi jik SMP. Otakku masih berkutat dengan nama-nama kerajaan di Indonesia. Jingseng!
Terlepas dari pengalaman nyelekit itu, saat kelas tiga SMP saya memiliki hobi main ke Solo sendirian. Yuhuu. Jadi ceritanya, setiap hari minggu saya pergi ke Gramedia dengan naik bus. Memang tidak langsung turun tepat di depan toko buku ternama itu. Sebab, tepat di depannya ada jalan searah yang harus dipatuhi. Alhasil, saya dari Kartasura turun di perempatan Gendengan atau kadang kelupaan mblabas sitihik sampai Lapangan Kota Barat.
Dari turun bus itulah saya memutuskan untuk jalan kaki hingga sampai di Gramedia. Pulangnya pun sama saja. Tingkah laku ini lumayan rutin saya lakukan setiap minggu, namun berakhir hingga awal-awal saya masuk SMA. Eits, jangan kira saya ke Gramedia buat beli buku. Ya cuma baca sampelnya dong, Bos. Cah irit og.
Begitulah kira-kira perkenalan saya dengan kota Solo semasa SMP. Sedang pengalaman saya ke Solo saat duduk di bangku SMA terhitung lebih sering tapi tidak rutin. Sebut saja misalnya kunjungan saya ke acara pensi, acara pameran komputer, acara lomba, serta mencari sponsor untuk acara ulang tahun sekolah.
Ada pula saat saya terlibat dengan komunitas menulis, eh tapi cuma datang pada satu kali rapat dan workshop. Niat hati ingin aktif benar, tapi keadaan kurang merestui. Sebab lokasi kumpul lebih jauh daripada tempat saya mbolos. Ya, tempat mbolos saya tak lain dan tak bukan adalah Balkon SGM, tempat main billyard. Jago billyard? Babar blas!
Oiya, tak luput dalam catatan juga jika saya pernah ngedate sama mbak-mbak kampus di Bakso Kadipiro. Ini lebih belagu daripada mbolos main billyard. Paginya saya baru banget punya SIM. Malamnya sok-sokan dinner. Pun masih harus nyasar dulu ketika dapat anceran kosnya belakang STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia), yang ternyata namanya sudah ganti jadi ISI (Institut Seni Indonesia).
Satu keentahan lagi antara saya dan Solo adalah saat terlibat acara HUT RI di THR Sriwedari. Saat itu saya dimintai bantuan untuh mengisi jumlah anggota Paskibra SMA yang kosong. Ya, Paskibra! Tubuh kurus kecil ini nyempil dalam barisan yang gagah-gagah itu. Dalam acara itu tugas saya ya cuma jalan berderap saja ketika dibutuhkan. Saya hampir seutuhnya lupa dengan acaranya seperti apa, sebab saya sibuk membetulkan celana pinjaman yang longgarnya minta ampyang.
Entahnya lagi, pulang dari acara itu sebagian dari kami memilih untuk mampir mall dengan tetap mengenakan seragram putih Paskibra. Hal yang kami lakukan di mall sungguh heroik sejati. Kami masuk ke dalam lift dari lantai atas. Berjajar rapi mengelilingi sisi lift dengan badan tegap dan muka serius. Barangkali sudah lima kali lift terbuka di beberapa lantai tapi kami tak gentar. Kami menolak untuk ke luar lift. Heroiknya di mana? Jangan salah sangka, kami secara sukarela membantu memencet tombol bagi pengunjung, lho.
Tentu saja biar praktis, kami pencet semua tombol. Mbois tenan po ra?
Selepas dari SMA saya kuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang jarak tempuhnya memakan waktu setidaknya setengah jam dengan naik motor. Bisa dibilang untuk pergi kuliah saya harus melewati keseluruhan Kota Solo. Sebab kampus saya letaknya jauh di timur berbatasan dengan Karanganyar. Maka kenyang sudah pengalaman saya melewati jalanan Solo.
Saking bosannya lewat jalan yang sudah saya hafal, ternyata muncul keisengan untuk memasrahkan laju motor kepada takdir. Jadi, ketika saya hendak mengunjungi suatu tempat, saya tidak lekas mengambil rute terdekat. Saya justru melupakan rutenya. Kalau ingin belok ya belok, kalau mau lurus ya lurus. Sewenang-wenang saja. Eloknya, sejauh ini saya selalu sampai pada tujuan tanpa rasa bosan di jalan.
Ngomong-ngomong soal jalanan, di Kota Solo ini fitur jalur searahnya sudah sampai tahap overdosis. Bahkan di lokasi-lokasi yang bagi saya cukup menggemaskan. Saking parnonya dengan jalan searah, saat melintas di jalan perkampungan pun selalu saya cari ada tanda jalan searah atau tidak. Maka benar saja jika dulu sempat terjadi demo penolakan jalan searah oleh warga Laweyan, sampai para demonstran ini menggelah sholat hajad di Jalan Dr. Radjiman.
Saya tak sanggup menuliskan semua detail pengalaman saya dengan Kota Solo saat mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Sudah barang tentu ada banyak sekali. Namun, dari sekian banyak itu tentu yang sering saya lakukan adalah memenuhi hasrat hiburan. Salah satunya kecanduan saya dengan bioskop.
Nonton film di bioskop seorang diri sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi saya. Saking sendirinya, saya pernah nonton Transcendence di XXI Solo Square pada pukul dua belas siang seorang diri. Seorang diri dalam arti sesungguhnya. Ya. Satu bioskop cuma saya yang nonton film itu. Seperetinya operator bioskop mengira bakal ada yang beli tiket Transcendence di belakang saya. E, ternyata hanya saya yang beli toket film Johny Deep.
Kegirangan nonton film di bioskop semakin gencar saat Hartono Mall menerapkan harga 10.000 rupiah sebagai biaya tiket untuk Platinum Cineplex. Itupun sudah bonus Big Cola mini. Tapi, lambat laun Platinum Cineplex merubah kebijakan harga. Dari yang semula 10.000 jadi naik 15.000, lalu 20.000, dan sekarang sudah menyentuh angka 25.000 sama dengan harga tiket XXI. Bedanya, Platinum Cineplex masih memberi bonus yang berupa pop corn. Ya. Akhirnya Platinum Cineplex sudah sadar jika bonus soft drink tidak meningkatkan pembelian pop corn. Tapi bonus pop corn bisa meningkatkan pembelian soft drink yang mahal. Bukan, begitu?
Satu keentahan lagi antara saya dan Solo adalah saat terlibat acara HUT RI di THR Sriwedari. Saat itu saya dimintai bantuan untuh mengisi jumlah anggota Paskibra SMA yang kosong. Ya, Paskibra! Tubuh kurus kecil ini nyempil dalam barisan yang gagah-gagah itu. Dalam acara itu tugas saya ya cuma jalan berderap saja ketika dibutuhkan. Saya hampir seutuhnya lupa dengan acaranya seperti apa, sebab saya sibuk membetulkan celana pinjaman yang longgarnya minta ampyang.
Entahnya lagi, pulang dari acara itu sebagian dari kami memilih untuk mampir mall dengan tetap mengenakan seragram putih Paskibra. Hal yang kami lakukan di mall sungguh heroik sejati. Kami masuk ke dalam lift dari lantai atas. Berjajar rapi mengelilingi sisi lift dengan badan tegap dan muka serius. Barangkali sudah lima kali lift terbuka di beberapa lantai tapi kami tak gentar. Kami menolak untuk ke luar lift. Heroiknya di mana? Jangan salah sangka, kami secara sukarela membantu memencet tombol bagi pengunjung, lho.
Tentu saja biar praktis, kami pencet semua tombol. Mbois tenan po ra?
Selepas dari SMA saya kuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang jarak tempuhnya memakan waktu setidaknya setengah jam dengan naik motor. Bisa dibilang untuk pergi kuliah saya harus melewati keseluruhan Kota Solo. Sebab kampus saya letaknya jauh di timur berbatasan dengan Karanganyar. Maka kenyang sudah pengalaman saya melewati jalanan Solo.
Saking bosannya lewat jalan yang sudah saya hafal, ternyata muncul keisengan untuk memasrahkan laju motor kepada takdir. Jadi, ketika saya hendak mengunjungi suatu tempat, saya tidak lekas mengambil rute terdekat. Saya justru melupakan rutenya. Kalau ingin belok ya belok, kalau mau lurus ya lurus. Sewenang-wenang saja. Eloknya, sejauh ini saya selalu sampai pada tujuan tanpa rasa bosan di jalan.
Ngomong-ngomong soal jalanan, di Kota Solo ini fitur jalur searahnya sudah sampai tahap overdosis. Bahkan di lokasi-lokasi yang bagi saya cukup menggemaskan. Saking parnonya dengan jalan searah, saat melintas di jalan perkampungan pun selalu saya cari ada tanda jalan searah atau tidak. Maka benar saja jika dulu sempat terjadi demo penolakan jalan searah oleh warga Laweyan, sampai para demonstran ini menggelah sholat hajad di Jalan Dr. Radjiman.
Saya tak sanggup menuliskan semua detail pengalaman saya dengan Kota Solo saat mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Sudah barang tentu ada banyak sekali. Namun, dari sekian banyak itu tentu yang sering saya lakukan adalah memenuhi hasrat hiburan. Salah satunya kecanduan saya dengan bioskop.
Nonton film di bioskop seorang diri sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi saya. Saking sendirinya, saya pernah nonton Transcendence di XXI Solo Square pada pukul dua belas siang seorang diri. Seorang diri dalam arti sesungguhnya. Ya. Satu bioskop cuma saya yang nonton film itu. Seperetinya operator bioskop mengira bakal ada yang beli tiket Transcendence di belakang saya. E, ternyata hanya saya yang beli toket film Johny Deep.
Kegirangan nonton film di bioskop semakin gencar saat Hartono Mall menerapkan harga 10.000 rupiah sebagai biaya tiket untuk Platinum Cineplex. Itupun sudah bonus Big Cola mini. Tapi, lambat laun Platinum Cineplex merubah kebijakan harga. Dari yang semula 10.000 jadi naik 15.000, lalu 20.000, dan sekarang sudah menyentuh angka 25.000 sama dengan harga tiket XXI. Bedanya, Platinum Cineplex masih memberi bonus yang berupa pop corn. Ya. Akhirnya Platinum Cineplex sudah sadar jika bonus soft drink tidak meningkatkan pembelian pop corn. Tapi bonus pop corn bisa meningkatkan pembelian soft drink yang mahal. Bukan, begitu?
 |
| Source: theparksolo.com |
Di sebelah Hartono Mall pun juga sama saja murahnya. Saat launch The Park Mall, bioskop XXI merayu para pengunjung dengan tiket nonton sebesar 15.000. Harga ini tetap konsisten selama beberapa bulan. Maka wajar saja jika saya sering nonton di sana. Secara kualitas memang lebih baik dari Platinum Cineplex, sih. Ah, nggedebus kamu, Ham. Hla wong kamu pilih The Park itu karena cuci matanya lebih bening, ya tho? Buktinya, kamu sering ke sana tapi cuma sekali doang makan.
Djancik! Gimana gak kapok? Siomay, mie ramen, dan dua minum saja totalnya tujuh puluh ribu! Dinggo ngeprint makalah filsafat lak yo nganti rampung sak semester jik jujul, Ndes.
Di samping foya-foya tak bernutrisi itu, saya juga mengagumi warung tenda di pinggir jalan. Warung-warung ini banyak yang baru buka tatkala sore telah tiba. Kuliner malam adalah salah satu hal yang eman-eman dilewatkan jika bertandang ke Solo. Mulai dari angkringan atau hik, warung bakso dan mie ayam, sate ayam, nasi liwet, nasi goreng, hingga susu segar asli Boyolali juga layak dijadikan tempat untuk mengisi perut.
Hik tetap menjadi andalan saya ketika kantong menipis atau saat sedang ingin menepi saja. Sebab di hik itu saya bisa terlibat obrolan ringan dengan orang-orang yang ada di situ meski tidak saling kenal. Mencoba macam-macam hik berbanding lurus dengan kebiasaan saya mencoba beraneka macam karakter. Kadang di hik wilayah Manahan saya bisa diam saja dari datang sampai pulang. Sedang di hik seputaran Laweyan saya bisa begitu supel. Sesuai mood saja.
Eh, tapi tenan lho. Obrolan-obrolan di hik itu kadang asu-asu bingit. Mulai dari yang serius yaitu komentar soal pembangunan Kota Solo, hingga masalah yang lebih serius lagi seperti kebimbangan untuk menyatakan cinta. Maka dari itu, syarat sahnya bakul hik itu ada tiga. Paham takaran gula, bisa membedakan mana nasi bandeng dan nasi oseng, serta menguasai psikoanalisis. Itu saja.
Sampai dengan detik ini saya puas dengan Kota Solo. Meski sempat jenuh dan timbul keinginan untuk hengkang, namun saya kira Solo sudah cukup sukses menimang saya senyaman ini. Tulisan kali ini saya dedikasikan untuk ulang tahun Kota Solo ke-272. Semoga makin nyaman, damai, kocak dan bisa meningkatkan produktivitas para pelaku kreatif.
Djancik! Gimana gak kapok? Siomay, mie ramen, dan dua minum saja totalnya tujuh puluh ribu! Dinggo ngeprint makalah filsafat lak yo nganti rampung sak semester jik jujul, Ndes.
Di samping foya-foya tak bernutrisi itu, saya juga mengagumi warung tenda di pinggir jalan. Warung-warung ini banyak yang baru buka tatkala sore telah tiba. Kuliner malam adalah salah satu hal yang eman-eman dilewatkan jika bertandang ke Solo. Mulai dari angkringan atau hik, warung bakso dan mie ayam, sate ayam, nasi liwet, nasi goreng, hingga susu segar asli Boyolali juga layak dijadikan tempat untuk mengisi perut.
Hik tetap menjadi andalan saya ketika kantong menipis atau saat sedang ingin menepi saja. Sebab di hik itu saya bisa terlibat obrolan ringan dengan orang-orang yang ada di situ meski tidak saling kenal. Mencoba macam-macam hik berbanding lurus dengan kebiasaan saya mencoba beraneka macam karakter. Kadang di hik wilayah Manahan saya bisa diam saja dari datang sampai pulang. Sedang di hik seputaran Laweyan saya bisa begitu supel. Sesuai mood saja.
Eh, tapi tenan lho. Obrolan-obrolan di hik itu kadang asu-asu bingit. Mulai dari yang serius yaitu komentar soal pembangunan Kota Solo, hingga masalah yang lebih serius lagi seperti kebimbangan untuk menyatakan cinta. Maka dari itu, syarat sahnya bakul hik itu ada tiga. Paham takaran gula, bisa membedakan mana nasi bandeng dan nasi oseng, serta menguasai psikoanalisis. Itu saja.
 |
| Source: qraved.co |
Header source: chic-id.com



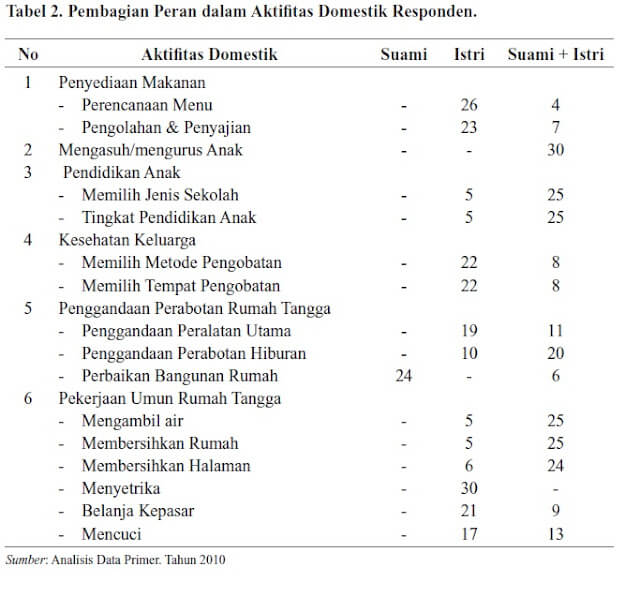
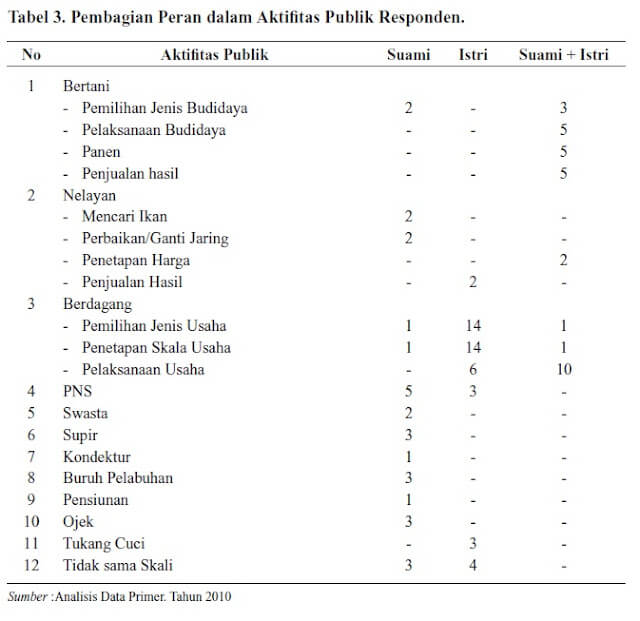
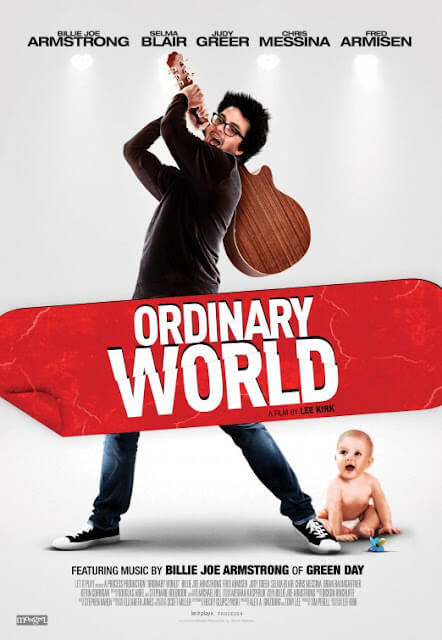






.jpg)