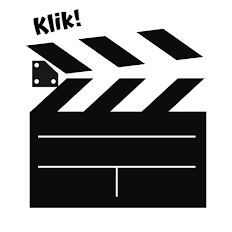Sejak Februari kemarin telah rilis sebuah film terbaru karya Joko Anwar, A Copy of My Mind. Layaknya Joko dalam film-film sebelumnya, kali ini ia (tentu) menyajikan karya yang benar-benar keluar dari tema-tema mainstream. ACMM adalah representasi kehidupan anak muda ‘susah’ di tengah Ibukota.
Sepasang kekasih yang tak biasa antara Alek (pembuat teks film bajakan) dan Sari (pekerja facial) yang sangat lugu, intim dan hyper ini sudah tentu tak terpikirkan dalam film Indo pada umumnya. Alek menjadi sosok yang amat dekat dengan kita mengingat sebagian besar dari kita pernah menyaksikan film bajakan dengan teks terjemahan yang jelek. Dan Sari dekat bagi mereka kaum perempuan karna pekerjaannya bersinggungan dengan eksistensi wanita sebagai simbol kecantikan duniawi.
Hubungan intim yang sering dikaitkan dengan film sampah tidak berlaku dalam ACMM. Berbeda dengan film-film Jupe yang kalau ada pakaian seksi dan adengan seks maka film itu terklaim ‘film sampah’ oleh masyarakat. Adengan seks menjadi mise-en-scene yang memang diperlukan dalam film ini. Seks bukan menjadi simbol gaya hidup glamor seperti NM dengan lingerie-nya dalam film....entahlah. Disini seks menjadi satu-satunya kenikmatan bagi mereka yang terhimpit sulitnya hidup dan enggannya mati. Adegan seks yang tidak didramatisir seperti adanya slow motion dan senandung lagu cinta membuat adegan ini lebih bermakna, apa adanya dan dingin.
Selain adegan seks yang tak perlu diwaspadai, adapula sisi religiusitas yang disinggung dalam ACMM. Seperti kumandang adzan subuh yang tidak lagi menjadi simbol panggilan sholat, tapi menjadi alarm gratis bagi Sari. Baginya kumandang adzan adalah saatnya bangun tidur agar bisa buruan antri kamar mandi mengingat ia tinggal di kos-kosan berpenduduk 100 dan berkamarmandi 10. Bagian adegan tersebut mengisyaratkan secara lugas betapa tidak ngefeknya kumandang adzan yang bersahut-sahutan jika manusianya tidak lagi memaknai seperti layaknya maksud adzan itu sendiri. Lebih radikal lagi terdapat scene saat Alek coly lalu serta merta digertak dengan kumandang adzan dari toa mesjid.
Tokoh Alek dan Sari adalah kita. Kita banget! Alek diceritakan tidak memiliki ktp, sim dan handphone, Alek adalah sosok tak beridentitas. Ia tinggal di kos yang ibu kosnya tidak pernah bicara. Alek adalah cerminan kita. Warga negara yang tidak terekam eksistensinya tapi sejatinya ia ‘ada’.
Sedangkan Sari pun demikian. Adalah pekerja yang berangkat pagi pulang sore. Adalah pekerja yang tidak nyaman dengan pekerjaannya tapi tak ada pilihan lain. Pekerja yang tidak mengikuti passion tapi bisa ahli dengan pekerjaannya. Sari adalah simbol ketidakberdayaan yang lari dari hidupnya dengan menonton film, sayangnya film bajakan, sebab Sari adalah kita yang tak mampu membeli eksklusifitas dan harus menikmati layanan kelas bawah yang tentu saja tak memuaskan.
Keadaan tersebut semakin tampak ketika Sari terlibat jauh dengan kasus suap antara pengusaha dan pejabat negara (capres bro). Tak pandang bulu, siapapun orangnya dan bagaimanapun hidupnya, semua yang membahayakan kaum penguasa harus disingkirkan. Begitulah kira-kira nasib Alek dan Sari. Ketika cinta membuat kebosanan mereka hilang kini kematian menunggu di depan pintu kosan.
A Copy of My Mind harus jadi film yang pernah anda tonton, bukan tentang 'bangga film Indonesia' tapi karena memang bagus.Nilai kehidupan yang paling aku suka dalam film ini adalah saat Alek menasehati Sari untuk jangan memilih film bajakan yang ada tulisan “combo format”, sebab (menurut Alek) combo format adalah film yang sudah berkali-kali di-copy, jadi kualitas gambarnya makin buruk. Demikian juga dengan kita bukan? Kalo terus menerus meng-copy orang lain hingga lupa siapa diri sendiri, lama kelamaan kualitas kita akan memburuk, dan mungkin saja hilang. Kehilangan jati diri, sikap, pemikiran dan kemerdekaan diri.







.jpg)