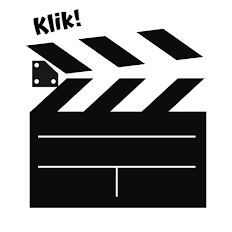Rilis pada tahun 2016, Sing Street memberi penyegaran bagi penonton film yang sebelumnya dimanja oleh film superheroes. Sing Street merupakan film racikan John Carney, yang dikenal sebagai seorang sutradara, penulis sekaligus komposer. Carney menjadikan tanah kelahirannya, Dublin (Irlandia), sebagai set dalam semesta film Sing Street itu sendiri. Dengan menguasai materi secara menyeluruh, Carney berhasil mendapat score bagus dari IMBD 8.1 dan Metascore 79 untuk Sing Street.
Sing Street bercerita tentang seorang remaja bernama Conor Lawlor (a.k.a Cosmo) yang mengalami berbagai tekanan, baik dari keluarga maupun lingkungan sekolahnya. Orangtua Conor mengalami kebangkrutan dari sektor ekonomi dan asmara. Ibunya yang diketahui selingkuh membuat suasana malam sering diramaikan oleh pertengkaran. Untung saja Conor memiliki kakak yang woles, Brendan Lawlor. Melalui Brendan inilah Conor mengenal dan mempelajari musik lengkap dengan falsafahnya.
Conor terpaksa belajar di sekolah baru demi menghemat biaya. Sayangnya, sekolah barunya ini semacam padepokan anak-anak badung. Sebagai murid baru yang terlihat lemah, Conor sudah pasti menjadi sasaran empuk para bullyers. Alih-alih mendapat perlindungan dari komite sekolah, Brother Bexter (Kepala Sekolah) pun turut serta memberi tekanan mental untuk Conor.
Di antara beragam tekanan yang Conor alami, beruntung lah ia bertemu dengan seorang perempuan yang tinggal tepat di seberang gerbang sekolah, Raphina. Perkenalan singkat yang penuh basa-basi absurd itu ternyata memberi dampak besar bagi kehidupan mereka berdua. Conor yang merasa hidupnya tak menarik berubah menjadi penuh gairah. Demikian juga dengan Raphina yang stuck dengan impiannya berubah lebih bersemangat dari sebelumnya.
Conor membuat kelompok band bernama ‘Sing Street’ demi mengesankan Raphina. Dari sini kita bisa melihat serunya membangun grup band, mulai dari perekrutan hingga rekaman. Bermacam kesalahan dan singgungan sudah pasti terjadi. Namun kuatnya cita akan menemukan jalannya.
Setiap babak yang disajikan dalam film ini merupakan representasi kehidupan yang sangat mudah dipahami. Seperti keputusan Conor untuk tampil idealis dengan rias wajah macam rock and roll ke sekolah. Teriakan ‘banci’ dan ejekan lain yang ditujukan untuknya dengan mudah ia acuhkan. Sayangnya, ditengah kuasa Brother Bexter lah idealisme Conor menguap bagai kuota telkomsel di antara YouTube dan insomnia.
Pertentangan yang paling menonjol dalam film ini bukanlah kontes musik macam Pitch Perfect. Melainkan pertentangan atas diri sendiri dalam mengambil setiap keputusan. Bukankah kita juga sering begitu, merasa ragu di tengah pilihan dalam hidup. Takut dengan akibat yang akan kita timbulkan jika salah mengambil keputusan. Ketakutan yang tidak bisa ditakhlukkan itu yang kemudian menjebak kita dalam zona nyaman. Masih mending sih kalau zona nyaman, parahnya lagi kalau terjebak di zona yang tidak kita sukai namun tak kuasa untuk beranjak dari sana.
Mencoba melawan intervensi yang terus menghantam, Conor menciptakan lagu-lagu sesuai dengan suasana hatinya. Besutan musik dari Eamon (gitaris) selalu memberi lantunan yang pas dengan semangat yang ingin dibawakan Conor dalam lagunya. Tak luput berkali-kali Brendan juga memberi arahan musik bagi Sing Street agar lagu yang diciptakan memiliki jiwa yang hidup di antara instrumen dan lirik. Lirik yang jujur dan musik bernas menjadi suara perlawanan baik itu melawan intervensi sekolah maupun melawan kemelut rasa cinta di pihak ketiga. #Eaaaaaa
Follow your dream adalah slogan yang tepat dalam film ini. Setiap orang pasti memiliki impian atau cita. Sebuah tujuan yang didambakan, diinginkan dan begitu dirindukan untuk dicapai. Sayangnya, tidak sedikit rintangan yang menghambat langkah kita untuk meraih sebuah impian. Masih mending hanya menghambat, beberapa diantara kita ada yang benar-benar terhenti dan merelakan impiannya menguap begitu saja.
Melalui Sing Street, saya memahami satu hal penting bahwa tidak semua orang yang mengejar passion itu bakal sukses mencapai impian. Lebih tepatnya tidak semua orang benar-benar sedang mengejar passion. Karena untuk ke arah sana perlu pengorbanan yang seringkali terlalu berat bagi sebagian orang. Dalam kasus ini, Conor berani melawan ketidakmungkinan yang mengekangnya. Dengan mempersetankan kepala sekolah dan keluarga yang retak, Conor menekuni dunia musiknya yang masih abu-abu.
Apakah yang dilakukan Conor mungkin kita tiru? Saya rasa sulit, sangat sulit. Bayangkan saja kamu benci dengan sekolah lalu memutuskan drop out demi mengejar passion-mu, misal ya bermusik itu. Pasti kamu takut dengan amarah orangtua, pertanyaan tak enak saudara dan cibiran tetangga. Belum lagi ketika keraguan muncul, misal kamu mulai membayangkan bagaimana jika kamu gagal. Tak ada ijasah yang bisa mem-backup di kemudian hari. Kurang takut apa lagi coba?
Itu juga masih dalam tingkat sekolah. Bahkan yang kuliah sekalipun sering juga terbentur tidak enak hati dengan keluarga. Lalu memaksakan diri menjadi mahasiswa meski hatinya di semesta yang berbeda. Ada beberapa mahasiswa yang bisa menjejali kehidupan kampusnya dengan upaya mengejar passion. Namun ada banyak yang pasrah membunuh impian-impiannya sendiri dan melakoni track kehidupan yang sudah ditentukan.
Membunuh impian itu sangat menyebalkan dan menyesakkan. Merasakan ketakberdayaan diri adalah prestasi paling memalukan dalam hidup. Saya iri dengan Conor yang sanggup memegang teguh tujuannya, mengejarnya, bahkan mempertaruhkan segalanya. Di samping itu, saya ini jenuh dengan motivasi follow your passion yang tidak aplikatif itu. Sebab tidak semua memiliki situasi yang memungkinkan untuk mengejar passion itu sendiri. Sah-sah saja bahkan bagus sekali jika kita mencoba untuk mengejar passion, asal harus siap dengan segala konsekuensi dan pertaruhan yang menanti.
Nilai-nilai kehidupan dalam film Sing Street inilah yang patut kita resapi lebih dalam. Hingga kemudian memunculkan beberapa pertanyaan seperti: Apa tujuan hidupku? Ke mana arah tujuan itu? Apa yang harus/ingin/bisa/suka aku lakukan untuk meraihnya? Apakah orang-orang di sekitar mendukungku? Apakah aku berjuang sendiri? Bagaimana aku melewati semua ini? Satu, dua atau lima tahun lagi aku akan seperti apa? Masih abu-abu kah atau mulai saat ini aku menggambarkannya?
Sing Street memang bagus untuk diseriusi. Namun, sebaiknya perlu sedikit rileks agar kejenakaan dalam film ini juga bisa dinikmati. Ada banyak sentilan-sentilan lucu yang nyelempit dalam dialog-dialongnya. Bagusnya, porsi lucu dan asmara diatur sedemikian pas hingga tidak mengaburkan esensi yang ditawarkan Sing Street. Dari yang saya paparkan di atas, sebenarnya masih ada nilai-nilai penting yang tidak bisa saya tuliskan semua.
Cukup sudah ocehan review saya tentang film Sing Street. Semoga ulasan saya mengenai Sing Street ini bermanfaat bagi kamu-kamu yang khusyuk membaca dari awal sampai kalimat ini. Jadi, kamu sudah nonton film ini belum? Yuk berbagi sudut pandang dengan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah berkenan mampir. Sampai jumpa di tulisan saya yang lain. Caoo!
Pict source: gannett-cnd.com










.jpg)