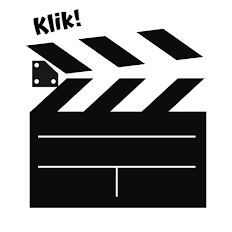Namaku Marco. Tapi bukan Marcopollo. Kau bisa memanggilku Markonthil jika lidahmu baik-baik saja. Meski sebenarnya tidak pernah ada yang memanggilku dengan sebutan itu. Sebab, aku tidak punya siapa-siapa selain satu orangtua. Aku tidak memiliki teman. Aku tidak menjalin hubungan apa-apa dengan lingkungan sosial.
Aku sadari ada sesuatu yang lain dalam diriku. Aku memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Aku memiliki perasaan yang begitu mendalam dan sering berubah-ubah. Kadang aku bersemangat. Kadang aku putus asa. Kadang keduanya beradu menjadi satu. Mereka menyebutku pasien bipolar.
Aku suka sekali saat mengalami manik. Manik membuatku lebih menyala, lebih bersemangat, lebih antusias dan lebih positif. Serta yang terpenting dari semua itu, manik membuatku mengerti bagaimana rasanya hidup. Namun sayang, orang-orang itu menyebutku gila. Mereka menuduhku berhalusinasi. Padahal bukan aku yang tak masuk akal. Tapi mereka saja yang terlalu bodoh untuk memahami perbedaan.
Aku benci dengan sistem. Jadi kuputuskan untuk keluar dari tempatku bekerja. Aku bisa bertahan hidup dengan berburu susu gratis di Starbucks dan memakan saus di McDonals. Tapi ayahku melarang. Ia datang ke apartemen dan memberi ceramah yang teramat membosankan. Aku muak. Aku kabur. Lalu kupanjat gedung bertingkat. Di atap gedung itu aku duduk terdiam. Memandang bulan yang begitu terang. Aku percaya apa yang kulakukan ini akan membawaku pada sensasi manik. Aku ingin melihat langit malam seperti lukisan Vincent van Gogh. Sayangnya, belum sempat kusaksikan Starry Night dengan kedua mataku, dua orang berseragam serba hitam menemukanku. Aku digiring ke kantor polisi.
Ayahku yang mengatur semuanya. Kini aku dikirim ke rumah sakit jiwa. Berkali-kali aku katakan pada mbokdhe psikiater itu jika aku tidak gila. Aku hanya bergairah. Tapi ia tidak mau mendengarkan. Pancen asu tenan wong-wong iku. Aku ini tidak gila. Kenapa kok aku dianggap dan diperlakukan sepeti orang gila?
Aku sadari ada sesuatu yang lain dalam diriku. Aku memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Aku memiliki perasaan yang begitu mendalam dan sering berubah-ubah. Kadang aku bersemangat. Kadang aku putus asa. Kadang keduanya beradu menjadi satu. Mereka menyebutku pasien bipolar.
Aku suka sekali saat mengalami manik. Manik membuatku lebih menyala, lebih bersemangat, lebih antusias dan lebih positif. Serta yang terpenting dari semua itu, manik membuatku mengerti bagaimana rasanya hidup. Namun sayang, orang-orang itu menyebutku gila. Mereka menuduhku berhalusinasi. Padahal bukan aku yang tak masuk akal. Tapi mereka saja yang terlalu bodoh untuk memahami perbedaan.
Aku benci dengan sistem. Jadi kuputuskan untuk keluar dari tempatku bekerja. Aku bisa bertahan hidup dengan berburu susu gratis di Starbucks dan memakan saus di McDonals. Tapi ayahku melarang. Ia datang ke apartemen dan memberi ceramah yang teramat membosankan. Aku muak. Aku kabur. Lalu kupanjat gedung bertingkat. Di atap gedung itu aku duduk terdiam. Memandang bulan yang begitu terang. Aku percaya apa yang kulakukan ini akan membawaku pada sensasi manik. Aku ingin melihat langit malam seperti lukisan Vincent van Gogh. Sayangnya, belum sempat kusaksikan Starry Night dengan kedua mataku, dua orang berseragam serba hitam menemukanku. Aku digiring ke kantor polisi.
Ayahku yang mengatur semuanya. Kini aku dikirim ke rumah sakit jiwa. Berkali-kali aku katakan pada mbokdhe psikiater itu jika aku tidak gila. Aku hanya bergairah. Tapi ia tidak mau mendengarkan. Pancen asu tenan wong-wong iku. Aku ini tidak gila. Kenapa kok aku dianggap dan diperlakukan sepeti orang gila?
Dengan jumlah masa yang begitu banyak sedangkan aku sendiri, jelas aku kalah suara. Tudingan mereka terhadapku dianggap sebuah fakta. Mau tidak mau aku harus terbiasa dengan sebutan gila yang melabeli namaku.
Aku dimasukkan ke dalam sebuah kelompok bipolar. Aku benar-benar dibuat bosan dengan kelompok ini. Sampai aku bertemu dengan seorang perempuan yang membuatku kesal, Carla. Carla begitu bodoh. Ia begitu pesimis dengan hidup ini. Aku benci orang sepertinya. Ia membuat hidupnya begitu sia-sia. Payah.
Suatu ketika, saat kami duduk berkelompok untuk menggambar, aku menjelaskan pada dua pria di hadapanku jika aku memiliki kemampuan untuk membuat syair dengan rima kompulsif. Manik yang kualami membuatku dapat menemukan dan menyusun kata-kata yang berima. Kemampuan ini sangat berguna bagiku untuk melakukan rap. Carla menantangku untuk melakukan freestyle rap. ia menyebut beberapa kata seperti “anti-kristus”, “tak tahu malu” dan “sendiri”. Kata-kata itu menjadi acuan untuk kujadikan bahan freestyle. Sepeti yang sudah sepantasnya terjadi. Aku menang. Aku membuatnya bungkam.
Lalu kulihat ia memegang sebuah buku. Aku rebut buku itu dari tangannya. Lalu kubaca syair yang tertulis di buku itu keras-keras. Carla meronta mencoba merebut bukunya. Tapi ia tak sanggup menjangkau dan aku masih melanjutkan membaca syair-syair itu. Tangan Carla terus mendesakku. Peganganku tak seimbang. Secara tak sengaja lipatan cover buku itu tersibak. Mataku terbelalak. Aku melihat siapa penulis buku itu.
Ternyata buku itu adalah kumpulan syair-syair yang ditulis Carla. Carla adalah seorang penyair. Sebagai pengidap bipolar, aku mengalami moodswing ekstrim seketika itu. Tiba-tiba mulutku tertutup rapat. Aku merasa bersalah telah mencoba mempermalukan karyanya.
Hari-hari setelah itu aku tak lagi mengganggunya. Kupikir dia adalah orang bodoh yang enggan memanfaatkan potensinya untuk sesuatu yang berharga. Ternyata ia lebih baik dariku. Kecanggungan sempat terjadi antara kami. Dan entah kenapa aku selalu memperhatikannya. Aku tertarik padanya.
Sesama bipolar, kami kerap terbangun bersama-sama tepat pukul tiga pagi. Tanpa ada perencanaan sebelumnya, kami berdua selalu menghabiskan sepertiga malam terakhir di ruang gambar. Kami beradu pendapat dan wawasan. Hingga akhirnya aku yakin pada rasa yang timbul tak terbantahkan. Aku jatuh cinta padanya. Dia pun sudah pasti begitu.
Aku dimasukkan ke dalam sebuah kelompok bipolar. Aku benar-benar dibuat bosan dengan kelompok ini. Sampai aku bertemu dengan seorang perempuan yang membuatku kesal, Carla. Carla begitu bodoh. Ia begitu pesimis dengan hidup ini. Aku benci orang sepertinya. Ia membuat hidupnya begitu sia-sia. Payah.
Suatu ketika, saat kami duduk berkelompok untuk menggambar, aku menjelaskan pada dua pria di hadapanku jika aku memiliki kemampuan untuk membuat syair dengan rima kompulsif. Manik yang kualami membuatku dapat menemukan dan menyusun kata-kata yang berima. Kemampuan ini sangat berguna bagiku untuk melakukan rap. Carla menantangku untuk melakukan freestyle rap. ia menyebut beberapa kata seperti “anti-kristus”, “tak tahu malu” dan “sendiri”. Kata-kata itu menjadi acuan untuk kujadikan bahan freestyle. Sepeti yang sudah sepantasnya terjadi. Aku menang. Aku membuatnya bungkam.
Lalu kulihat ia memegang sebuah buku. Aku rebut buku itu dari tangannya. Lalu kubaca syair yang tertulis di buku itu keras-keras. Carla meronta mencoba merebut bukunya. Tapi ia tak sanggup menjangkau dan aku masih melanjutkan membaca syair-syair itu. Tangan Carla terus mendesakku. Peganganku tak seimbang. Secara tak sengaja lipatan cover buku itu tersibak. Mataku terbelalak. Aku melihat siapa penulis buku itu.
Ternyata buku itu adalah kumpulan syair-syair yang ditulis Carla. Carla adalah seorang penyair. Sebagai pengidap bipolar, aku mengalami moodswing ekstrim seketika itu. Tiba-tiba mulutku tertutup rapat. Aku merasa bersalah telah mencoba mempermalukan karyanya.
Hari-hari setelah itu aku tak lagi mengganggunya. Kupikir dia adalah orang bodoh yang enggan memanfaatkan potensinya untuk sesuatu yang berharga. Ternyata ia lebih baik dariku. Kecanggungan sempat terjadi antara kami. Dan entah kenapa aku selalu memperhatikannya. Aku tertarik padanya.
Sesama bipolar, kami kerap terbangun bersama-sama tepat pukul tiga pagi. Tanpa ada perencanaan sebelumnya, kami berdua selalu menghabiskan sepertiga malam terakhir di ruang gambar. Kami beradu pendapat dan wawasan. Hingga akhirnya aku yakin pada rasa yang timbul tak terbantahkan. Aku jatuh cinta padanya. Dia pun sudah pasti begitu.
Kami berdua menjalin hubungan asmara yang biasa saja. Tidak ada pesta, kemegahan, maupun sorak-sorai dari teman-teman yang mendukung. Aku dan Carla hanya menyelami cinta sebagaimana yang kami tahu. Kami ingin berdua terus-menerus. Itu saja.
Entah kenapa orang-orang di sekitar kami lah yang repot. Orangtua Carla menentang hubungan kami. Mereka pikir aku terlalu gila. Baiklah aku sudah terbiasa dengan sebutan gila. Tapi apa mereka tidak bisa membuka mata dan melihat bagaimana Carla bahagia bersamaku. Mereka bodoh sekali. Sudah bodoh, belagak tahu pula. Aku dan Carla sudah saling mencinta. Tidak perlu pakai logika rendah yang mencoba menjelaskan betapa beresikonya hubungan ini. Sebab aku dan Carla mencinta sebagai sesama pengidap bipolar. Kami berdua memiliki perasaan yang begitu dalam. Sehingga kami tidak mengenal cinta dalam konsep-konsep rasionalitas.
Hubunganku dan Carla terasa menyenangkan. Aku yang lebih sering dan sangat ingin mengalami manik membuat hubungan kami terasa berapi-api, bertujuan dan menyenangkan. Sedangkan, Carla yang dominan dengan depresifnya seperti menghujani hari yang panas. Meneduhkan, menyegarkan dan membuatku lebih tenang. Aku heran dengan orangtua Carla yang terus-menerus mengambil keputusan sepihak untuk anaknya. Hal ini tentu membuat Carla semakin hanyut dalam episode depresinya. Jika aku tak salah ingat, dalam Mourning and Melancholia yang ditulis Sigmund Freud mengatakan bahwa potensi depresi diciptakan dari periode oral. Maksudnya, waktu anak mulai belajar berbicara. Aku meyakini pasti Carla kecil melihat ketidakharmonisan di keluarganya saat itu. Tanpa disadari, Carla menyerap ketakutan dan keputusasaan yang membuat psikisnya terganggu. Ah, ini hanya dugaanku saja. Aku sama sekali tidak peduli dengan Carla di masa lalu. Aku mencintai Carla saat ini. Itu saja.
Tapi asu!
Entah kenapa orang-orang di sekitar kami lah yang repot. Orangtua Carla menentang hubungan kami. Mereka pikir aku terlalu gila. Baiklah aku sudah terbiasa dengan sebutan gila. Tapi apa mereka tidak bisa membuka mata dan melihat bagaimana Carla bahagia bersamaku. Mereka bodoh sekali. Sudah bodoh, belagak tahu pula. Aku dan Carla sudah saling mencinta. Tidak perlu pakai logika rendah yang mencoba menjelaskan betapa beresikonya hubungan ini. Sebab aku dan Carla mencinta sebagai sesama pengidap bipolar. Kami berdua memiliki perasaan yang begitu dalam. Sehingga kami tidak mengenal cinta dalam konsep-konsep rasionalitas.
Hubunganku dan Carla terasa menyenangkan. Aku yang lebih sering dan sangat ingin mengalami manik membuat hubungan kami terasa berapi-api, bertujuan dan menyenangkan. Sedangkan, Carla yang dominan dengan depresifnya seperti menghujani hari yang panas. Meneduhkan, menyegarkan dan membuatku lebih tenang. Aku heran dengan orangtua Carla yang terus-menerus mengambil keputusan sepihak untuk anaknya. Hal ini tentu membuat Carla semakin hanyut dalam episode depresinya. Jika aku tak salah ingat, dalam Mourning and Melancholia yang ditulis Sigmund Freud mengatakan bahwa potensi depresi diciptakan dari periode oral. Maksudnya, waktu anak mulai belajar berbicara. Aku meyakini pasti Carla kecil melihat ketidakharmonisan di keluarganya saat itu. Tanpa disadari, Carla menyerap ketakutan dan keputusasaan yang membuat psikisnya terganggu. Ah, ini hanya dugaanku saja. Aku sama sekali tidak peduli dengan Carla di masa lalu. Aku mencintai Carla saat ini. Itu saja.
Tapi asu!
Orang-orang semakin gencar menjauhkanku dari Carla. Memaksaku minum obat-obat tai kucing itu. Sudah kubilang berkali-kali jika aku tak akan minum obat. Karena obat itu tidak membuatku menjadi lebih baik. Untuk kali ini saja, kenapa tak ada seorang pun yang mendukung keteguhanku? Bahkan Carla.
Pada akhirnya Carla terlalu putus asa dengan hubungan kami yang selalu ditentang. Carla berhenti berontak. Ia minum obat dengan rutin. Aku benci dengan Carla yang sekarang. Ia berubah menjadi manusia yang membosankan. Manusia yang terlalu banyak memikirkan tetek bengek sampai secara sukarela memadamkan perasaannya. Manusia yang terlalu banyak berpikir dan lupa untuk merasa.
Aku tak mengerti lagi. Carla sudah berubah menjadi orang yang tak kukenal. Ia lebih memilih menjadi sosok yang diharapkan ibunya sampai-sampai membunuh Carla yang asli. Pada titik ini aku menyerah. Aku memutuskan untuk pergi dari hidupnya. Aku menghilang saja. Cinta sudah sirna. Kini aku sebatang kara.
Pada akhirnya Carla terlalu putus asa dengan hubungan kami yang selalu ditentang. Carla berhenti berontak. Ia minum obat dengan rutin. Aku benci dengan Carla yang sekarang. Ia berubah menjadi manusia yang membosankan. Manusia yang terlalu banyak memikirkan tetek bengek sampai secara sukarela memadamkan perasaannya. Manusia yang terlalu banyak berpikir dan lupa untuk merasa.
Aku tak mengerti lagi. Carla sudah berubah menjadi orang yang tak kukenal. Ia lebih memilih menjadi sosok yang diharapkan ibunya sampai-sampai membunuh Carla yang asli. Pada titik ini aku menyerah. Aku memutuskan untuk pergi dari hidupnya. Aku menghilang saja. Cinta sudah sirna. Kini aku sebatang kara.
 |
| Carla (Katie Holmes) touchedwithfire.com |
Berangkat dari buku berjudul Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament (1992), ditulis oleh Kay Jamison, telah berhasil diolah dengan baik menjadi sebuah film yang memunculkan kisah asmara Marco dan Carla. Touched with Fire garapan Paul Dorio sukses mengemas psikologi, sastra dan seni dalam cerita romance yang menyenangkan sekaligus mengharukan. Film ini didedikasikan kepada seniman, penulis dan musisi pengidap bipolar yang tercantum dalam bukunya Kay Jamison.
Source banner: touchedwithfire.com/
Source banner: touchedwithfire.com/