Detakan waktu berjalan dengan tenang. Iramanya tak pernah berubah sejak aku memasuki ruangan ini 10 tahun yang lalu. Aroma yang sangat kukenal membungkam nafasku. Tekanan udara terasa tebal dan berat, meremas tubuh kecilku yang padat dengan kuat. Tempat ini menolak kepergianku. Mereka nyaman bersamaku. Setiap rasa lelah, resah dan amarah selalu saja mereka menemaniku. Bahkan tembok-tembok putih itu sangat senang ketika permainan baku hantam kupilih ia sebagai lawanku. Kapuk-kapuk yang setiap malam bercinta dibawah rebahan tubuhku. Nyanyian merdu dari deritan almari yang setiap hari merebus gendang telingaku telah menjadi hal yang biasa. Selama bertahun tahun tempat ini menjadi markas besarku. Sebuah post rahasia. Tempat dimana aku bertransaksi dengan tawa, amarah dan air mata.
Satu persatu helai kain kumasukan dalam sebuah peti, terlihat seperti koper tapi terlalu tua. Ransel usang yang menjadi sahabat sekolahku dulu merasa cemburu. Ia menatapku dari ujung ranjang dengan sinis. Kepalanya menunduk seolah sedang berkabung. Hatiku tak tega. Kuhampiri. Ku genggam bahunya dan kuangkat kepunggungku. “Ayo kemarilah,” sebuah cermin yang menempel dipintu almari tua itu memanggilku. Kulihat dengan jelas bayangan semu dibalik bola mata cermin itu. Sesosok pria kecil yang beranjak dewasa sedang menggendong ransel usang yang penuh luka jahitan dan tempelan kain-kain tak bernyawa. Bahkan aku masih pantas mengenakan ini.
Krriiiieeeeekk.....
Suara gesekan engsel pintu berirama menjadi sinyal bahwa markas sedang diserang. Ya, seseorang membuka pintu kamarku. Sosok seorang perempuan berjilbab tipis itu menghampiriku. Ia duduk ditepian ranjang yang sudah kurapihkan. Melihatku dengan tatapannya yang sayu. Hening dan sunyi. Hanya suara kecil dari kesibukanku menata rapi bekal masa depanku di dalam ransel.
Akhirnya kebekuan itu meleleh. Suara resleting ransel yang melengking panjang mengisyaratkan sesuatu.
“Masih ada yang kelupaan gak?”
“Sudah semua. Kurasa ini cukup. Lagian aku ini kan cowok, tak perlu ribet ini itu bu. Hehehe”
“Sebelum berangkat jangan lupa berdoa. Itu Ibu sudah buatin sarapan. Mending kamu makan dulu sebelum berangkat.”
“Iya bu. Agus tak akan jera berdoa. Ibu telah mengajarkan banyak hal, termasuk berdoa. Dan dari doa itulah Agus percaya bahwa keajaiban itu ada. Keajaiban itu bukan sebuah keberuntungan tapi jawaban dari setiap doa kita. Tuhan Maha Mengetahui. “
“Iya nak. Dan kau adalah jawaban dari doa ibu yang paling ibu sayangi. Kamu disana jangan macam-macam ya. Jangan lupa solat dijaga.”
Bibirku tertarik membentuk lengkungan indah diwajahku. Ini memang bukan pertemuan terakhirku dengan Ibu, tapi kecemasannya adalah kekuatan cinta yang ia beri untukku. Kecemasannya akan bermetamorfosis menjadi doa disetiap sujudnya. Untukku. Anak semata wayangnya.
Seperti atap yang bocor, air mata itu akhirnya menyeruak keluar dengan paksa. Menyapu pipi kisutnya oleh kerasnya air mata yang mengombak. Dengan sekejab tubuh kami menjadi satu. Satu pelukan erat yang basah air mata. Nasehatnya belum berhenti. Ia mengatakan sesuatu yang tak aku mengerti. Suaranya parau diantara sesenggukan nafasnya. Kata per katanya tersenggal tak menentu. Aku hanya memeluknya erat. Aku tahu ada doa disetiap suku katanya yang berjeda.
Tanpa ku tahu sejak kapan, sesosok lelaki memenuhi mulut pintu kamar. Berdiri tegap terlihat tegas dan berani. Ditangan kanannya tergenggap sebuah kain tebal hitam yang terlipat tak rapi. Ia menghampiriku. Menepuk pundak Ibu dan menariknya perlahan.
“Sudah bu, jangan biarkan anak kita merasa berat meninggalkan rumah ini.”
Air mata ibu mulai meresap kering. Ibu terdiam. Mencoba untuk mengatur kembali nafasnya. Sibakan jari jemarinya membersihkan air mata dari pipinya.
“Ini Nak. Pakailah.”
“Ini jaket siapa, Pak”
“Ini Nak. Pakailah.”
“Ini jaket siapa, Pak”
“Itu jaket bapak. Tidak pernah bapak pakai karna terlalu kecil. Sekarang pakailah. Meski sudah tua tapi tetap hangat. Pakailah untuk menepis air hujan.”
Jari jemari kasarnya sempat kurasakan saat jaket itu beralih tangan padaku.
“Bapak tidak usah khawatir. Agus pasti pakai jaket Bapak ini. Jaket ini tidak hanya untuk menepis hujan, tapi Agus juga akan kenakan ketika kuliah ato ketika berpergian.”
“Apa kamu gak malu pake jaket tua itu?”
“Tak ada yang membuatku malu dari perwujudan kasih sayang orangtua padaku.”
“Kamu telah dewasa. Baik bapak tunggu kamu di meja makan. Kita sarapan dulu bersama, baru kamu berangkat. Oke?”
“Siap..” sahutku dengan senyum bangga.
Namaku Agus Saputro. Terlahir dari keluarga kecil yang sederhana. Usiaku menginjak 18 tahun dan kini akan mengenyam pendidikan ke negeri tetangga, Singapore University of Technology and Design. Orangtuaku seorang pedagang. Toko kelontong kecil depan rumahku adalah arus rejekinya. Sesekali di hari minggu Ibu menjajakan makanan ringan di pasar. Pendapatannya memang tak seberapa, tapi rasa syukur atas semua yang mereka miliki sungguh luar biasa. Mereka tak pernah mengeluh. Sekali duakali kena tipu dan uang palsu pun mereka rasakan.
Aku percaya bahwa keajaiban itu ada. Dan datang seiring terpanjatkannya sebuah doa. Masa-masa seragam sekolah kulewati dengan beasiswa. Dan kini prestasi menuntutku untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Singapore akan menjadi markasku yang kedua. Tempatku meraih cita-cita. Akulah hasil jerih payah Ibu. Akulah penyandang nama Ayah. Tak ada alasan untuk mengecewakan mereka.
“Bapak tidak usah khawatir. Agus pasti pakai jaket Bapak ini. Jaket ini tidak hanya untuk menepis hujan, tapi Agus juga akan kenakan ketika kuliah ato ketika berpergian.”
“Apa kamu gak malu pake jaket tua itu?”
“Tak ada yang membuatku malu dari perwujudan kasih sayang orangtua padaku.”
“Kamu telah dewasa. Baik bapak tunggu kamu di meja makan. Kita sarapan dulu bersama, baru kamu berangkat. Oke?”
“Siap..” sahutku dengan senyum bangga.
Namaku Agus Saputro. Terlahir dari keluarga kecil yang sederhana. Usiaku menginjak 18 tahun dan kini akan mengenyam pendidikan ke negeri tetangga, Singapore University of Technology and Design. Orangtuaku seorang pedagang. Toko kelontong kecil depan rumahku adalah arus rejekinya. Sesekali di hari minggu Ibu menjajakan makanan ringan di pasar. Pendapatannya memang tak seberapa, tapi rasa syukur atas semua yang mereka miliki sungguh luar biasa. Mereka tak pernah mengeluh. Sekali duakali kena tipu dan uang palsu pun mereka rasakan.
Aku percaya bahwa keajaiban itu ada. Dan datang seiring terpanjatkannya sebuah doa. Masa-masa seragam sekolah kulewati dengan beasiswa. Dan kini prestasi menuntutku untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Singapore akan menjadi markasku yang kedua. Tempatku meraih cita-cita. Akulah hasil jerih payah Ibu. Akulah penyandang nama Ayah. Tak ada alasan untuk mengecewakan mereka.
Sahabat ransel dipunggungku. Koper tua ditangan kananku. Jam tangan penuh goresan melingkar di tangan kiriku. Jaket hitam lusuh ditubuhku. Tali sepatu bekas lumpur terikat kencang. Rambut tipis tersapu kesamping. Kutegapkan dadaku. Kuhimpun semangat dan niatku. Untuk waktu yang cukup lama akanku tinggalkan tempat ini. Bola mata hitam berotasi menjamah setiap sudut ruang dan benda yang terpampang rapi.
Kujabat erat daun pintu kamarku. “Sampai jumpa kolonel. Terimakasih telah menjaga markas ini dengan baik. Sampaikan salamku pada yang lain.”
Hanya senyum, caraku berpaling dari rasa rindu.
Kujabat erat daun pintu kamarku. “Sampai jumpa kolonel. Terimakasih telah menjaga markas ini dengan baik. Sampaikan salamku pada yang lain.”
Hanya senyum, caraku berpaling dari rasa rindu.

.png)




.jpg)


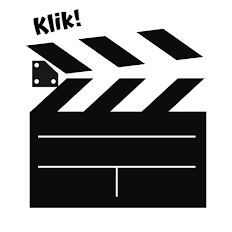

Tidak ada komentar:
Posting Komentar